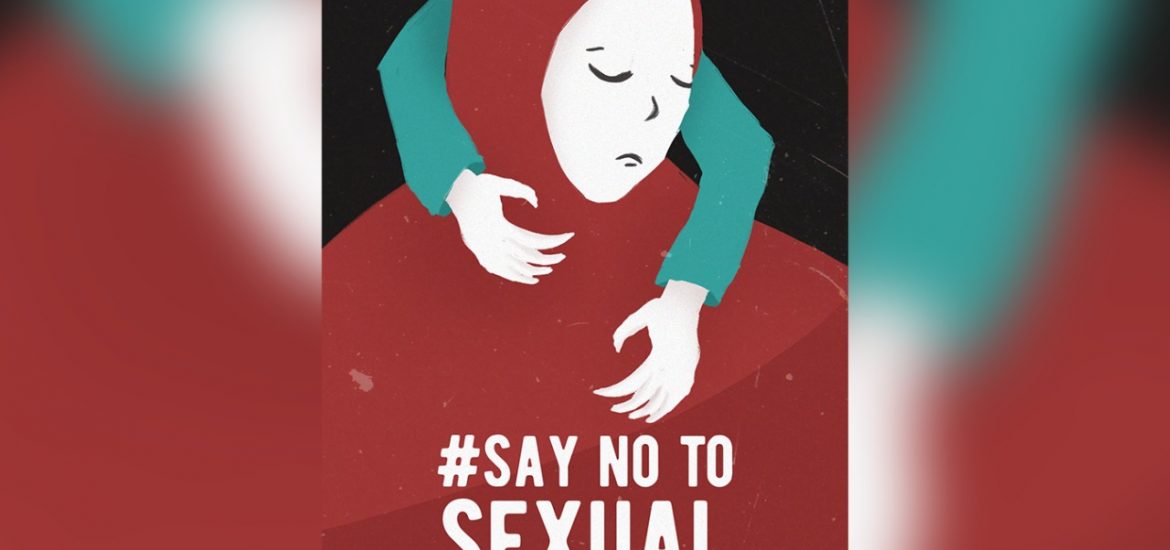Mediasolidaritas.com – Maju kena mundur kena. Bak buah Simalakama, rasa traumatis dan dilematis dialami korban pelecehan seksual yang tidak mendapatkan ruang aman. Terlebih, regulasi terkait kekerasan seksual juga tak kunjung disahkan.
“Rasanya sangat malu, saya merasa tidak bisa menjaga diri dengan baik. Saya juga merasa kotor, hina, dan berdosa. Sampai berpikiran, saya ingin ganti badan. Saya takut untuk berangkat sekolah. Sering merasa stres dan tiba-tiba nangis sendiri. Saya butuh perlindungan,” ujar Laila (bukan nama sebenarnya) yang saat ini aktif dalam gerakan perempuan di Jawa Timur.
Dengan raut wajah sedih, Laila menceritakan bagaimana dia mendapat perlakuan pelecahan seksual oleh temannya semasa menduduki bangku sekolah. Rasa trauma itu, terus membekas dalam benaknya.
Konselor Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak kota Surabaya Ani mengungkapkan, rasa trauma dan stres pada korban pelecehan seksual memang rentan terjadi. Ketika seseorang mengalami pelecehan seksual, yang dibutuhkan pertama adalah pendampingan dan dukungan bahwa korban tidak sendirian. Selain itu, korban juga berhak mendapat keadilan dengan menyuarakan apa yang dialaminya sehingga bisa menjadi pahlawan bagi korban pelecehan seksual lainnya.
Namun, menurut Ani hal itu tentu tidak mudah. Karena korban akan merasa takut atau ragu ketika ingin bersuara. Padahal, upaya tersebut perlu dilakukan supaya pelaku tidak merasa aman aman saja setelah melakukan pelecehan seksual.
“Kalau korban tidak berani untuk berbicara, pelaku juga tidak akan berhenti. Mungkin, suatu saat korban bisa berdamai dengan rasa traumanya, tapi dari sisi pelaku pasti akan ada korban-korban selanjutnya,” terangnya saat diwawancarai pada Selasa (31/8).
Ketua Asosiasi Wanita Gender (ASWG) yang juga merupakan dosen Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) Anis Farida memaparkan, Faktor yang membuat korban tidak berani bersuara dipengaruhi oleh kultur masyarakat yang menjunjung tinggi nilai moral. Selain itu, korban pelecehan seksual malah mendapatkan stigma negatif.
“Dalam kultur masyarakat beragama dan menjunjung tinggi nilai moral, membuat korban berpikir ribuan kali untuk berani bersuara. Apakah nanti orang akan percaya atau justru malah timbul persepsi mengapa tidak berhati-hati dan malah dianggap karena berpakaian yang mengundang. Padahal tidak semua konteks demikian,” jelas Farida pada Jum’at (3/9).
Relasi yang sifatnya hierarki juga membuat korban lebih memilih untuk diam. Dalam pelbagai lingkup, termasuk dalam hubungan keluarga yang terjadi justru orang tua menyalahkan anaknya karena dianggap tidak mampu menjaga dirinya.
“Faktor hierarki ini berpengaruh besar pada korban. Biasanya demi menjaga nama baik organisasi atau bahkan keluarga. Daripada nama baiknya tercemar akhirnya korban memilih menutup rapat-rapat,” tandasnya.
Dengan kompleksnya permasalahan pelecehan seksual yang terjadi, Farida berharap melalui edukasi, membangun kultur, serta membangun struktur melalui instrumen perundang-undangan seperti pengesahan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) dan juga Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan (PERMENDIKBUD) Kekerasan seksual di kampus dapat menjadi solusi dalam maraknya kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus.
PERMENDIKBUD tentang Kekerasan Seksual di Kampus sendiri merupakan gagasan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (MENDIKBUD-RISTEK) Nadiem Makarim. Regulasi tersebut disiapkan guna mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual di lingkungan kampus. Dalam konsepnya nanti, akan dibentuk suatu gugus tugas yang mempunyai satu divisi pelayanan kepada mahasiswa yang mengalami pelecehan seksual di kampus.
Gugus tugas nantinya diharapkan dapat bertindak independen seandainya terjadi kasus pelecehan seksual. Anggotanya pun diisi dengan seseorang yang mempunyai track record di bidang aktivis gender.
“Permasalahannya kan apa bisa gugus tugas ini dibentuk dalam struktur, tetapi waktu saya rapat dengan Nadiem menyarankan jika nanti gugus tugas mengalami kebuntuan dalam tugasnya maka tim tersebut bisa langsung mengkomunikasikan kepada MENDIKBUD–RISTEK. Tetapi juga PERMENDIKBUD ini kan hingga saat ini belum kunjung disahkan,” terang Farida.
Kebijakan Kampus Perihal Pelecehan Seksual
UINSA sendiri sebenarnya sudah mengatur mekanisme mengenai pelecehan seksual. Hal itu tertuang dalam Keputusan Rektor UINSA No. 378 tahun 2017 bab VI pasal 10 ayat 2 huruf h. Dalam kode etik tersebut mahasiswa dilarang melakukan berbagai tindakan pelanggaran seperti berjudi, minum minuman memabukkan, melakukan tindakan pergaulan bebas, perzinahan, pemerkosaan, pencabulan, berkhalwat dan aborsi illegal. Bentuk sanksi yang diberikan pun bermacam macam.
Merujuk pada bab VII pasal 14 ayat 2 pergaulan bebas yang dimaksud adalah perbuatan tidak senonoh, melanggar kesopanan, etika dan ajaran agama seperti bercumbu dengan sejenis atau lawan jenis serta tindakan serupa lainnya. Pelanggaran tersebut akan dikenai sanksi berupa teguran dan skorsing selama dua semester.
Perzinahan dalam pasal ini dikategorikan dengan hubungan intim seksualitas diluar ikatan perkawinan. Jika hal itu terbukti maka hukuman yang diberikan berupa Drop Out (DO) atau dinyatakan gugur dan dicabut gelar ijazahnya. Hukuman tersebut berlaku pula untuk pelaku tindakan pemerkosaan. Bahkan, kampus juga akan melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwajib. Perbuatan cabul dan berkhalwat dikenakan sanksi berupa teguran baik lisan maupun tertulis.
Menurut rektor UINSA Prof Masdar Hilmy, hukuman atau sanksi diterapkan dengan melihat tingkat pelanggaran yang dilakukan. Jika pelanggaran tersebut berdampak hingga korban mengalami kerusakan (kehamilan, cacat, -red) maka hukumannya jauh lebih berat. Namun, untuk kerusakan psikis seperti trauma maupun stres, Prof Masdar Hilmy mengatakan hal itu masih belum dapat dibuktikan karena sifatnya yang subjektif.
“Kalau untuk kerusakan mental maka hal itu perlu dikaji lebih lanjut. Tapi semua nanti tergantung pada anggota mahkamah etik,” ujar Prof Masdar Hilmy saat ditemui di ruangannya.
Mahkamah etik ini nantinya akan dibentuk jika ditemukan pelanggaran serta laporan kepada pihak kampus. Ada beberapa klasifikasi kasus yang dapat dilaporkan kepada mahkamah etik. Yakni jika kasus tersebut tidak bisa diredam secara kekeluargaan dan terdapat pihak yang merasa keberatan.
Prof Masdar Hilmy pun mengaku akan menjamin tentang kerahasiaan korban seandainya ia mendapat laporan mengenai adanya kasus pelecehan seksual. Ia juga mengatakan korban dapat langsung mengirim surat kepadanya selaku rektor dan nantinya akan diproses sesuai prosedur. Selain itu, korban juga dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang di fakultas terkait.
Dukungan Moral Oleh Kampus Kepada Korban Pelecehan Seksual
Adanya kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus turut mengundang perhatian Kepala Bidang Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), dan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya Ida Widayati.
Dia menyarankan agar perguruan tinggi dapat menyediakan tempat layanan konseling terhadap kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Sehingga nantinya korban dapat tertangani dengan baik.
Sementara itu, Dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan (FPK) UINSA, Siti Nur Asiyah mengatakan bahwa selama ini FPK belum pernah menangani kasus pelecehan seksual.
“Kalau ruang konseling laboratorium psikologi itu. Tapi lab itu untuk mahasiswa FPK. Kalau ada mahasiswa yang ingin konsultasi bisa dan tidak harus di ruangan itu. Mahasiswa cukup menghubungi dosen untuk menceritakan masalahnya lalu janjian,” katanya. (Dam/Izz)